Ditulis oleh I. Fadilah, B.A. Djaafara, K. Saraswati, F. Verisqa, Nursidah, R. Maulida, F. Andiwijaya
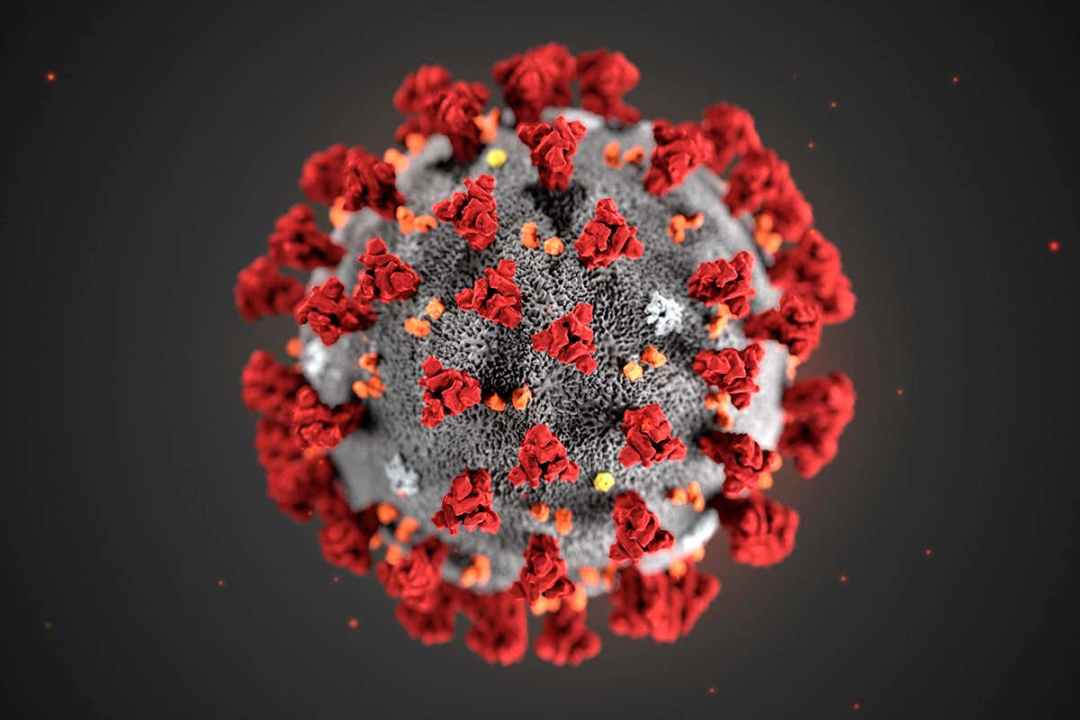
Pada tanggal 11 Januari 2021, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan pemberian Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia untuk vaksin CoronaVac dari perusahaan Sinovac Biotech1. EUA diberikan dengan mempertimbangkan hasil interim uji klinis di Indonesia, Turki, dan Brazil. Pemerintah menyebutkan bahwa hasil interim uji klinis CoronaVac yang dilakukan di Bandung memiliki efikasi (kemanjuran) sebesar 65,3% [1], berbeda dibandingkan dengan uji klinis vaksin CoronaVac di lokasi-lokasi lain yaitu Brazil (50,38% [3,4,5]) dan Turki (91,25% [6]).
Ada beberapa aspek dan konsep dari hasil uji klinis ini yang perlu penjelasan lebih lanjut. Selain itu, di akhir konferensi pers pengumuman EUA tersebut, ada beberapa poin penting yang ditanyakan oleh wartawan, diantaranya:
- Apa arti dari efikasi 65,3%?
- Mengapa efikasi uji klinis di Indonesia berbeda dibanding di lokasi lain?
- Apakah sudah bisa meninggalkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) setelah mendapatkan vaksin?
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait.
Apa arti efikasi 65,3%?
Efikasi vaksin dalam uji klinis fase 3 mengukur seberapa baik vaksin dalam mencapai tujuan utama (primary endpoint) dalam suatu uji klinis (dalam keadaan terkontrol atau konteks penelitian). Efikasi dapat diartikan sebagai pengurangan risiko di kelompok yang diberi vaksin, dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan plasebo (tidak mendapat kandungan vaksin), dalam suatu uji klinis.
Hasil interim uji klinis vaksin-vaksin Covid-19 yang sudah dirilis sejauh ini memiliki primary endpoint salah satunya: apakah vaksin yang diuji dapat mencegah infeksi SARS-CoV-2 bergejala (Covid-19 ringan dan parah)? [2] Jika efikasi uji klinis sebesar 65,3% artinya terjadi pengurangan risiko Covid-19 bergejala sebesar 65,3% di populasi yang mendapatkan vaksin dibandingkan yang mendapatkan plasebo.
Dalam konteks hasil uji klinis ini, belum dapat dipastikan seberapa besar efikasi vaksin yang diberikan dalam mengurangi risiko infeksi virus SARS-CoV-2 yang tidak bergejala dan mengurangi risiko penularan/transmisi. Namun, perlu diketahui juga bahwa berdasarkan hasil uji vaksin CoronaVac di Brazil [3,4,5,] tidak ditemukan adanya Covid-19 dengan gejala parah (memerlukan perawatan di rumah sakit) di kelompok orang yang mendapatkan vaksin (meskipun kita masih perlu melihat interval kepercayaannya).
Temuan di Brazil ini, dengan efikasi klinis keseluruhan 50,38% [5], ditambah dengan hasil efikasi interim di Turki sebesar 91,25%6, memberikan bukti tambahan bahwa CoronaVac memiliki kemampuan mencegah keparahan gejala akibat infeksi virus SARS-CoV-2 yang cukup baik.
Mengapa efikasinya berbeda-beda di tiap negara?
Setidaknya, ada tiga alasan yang dapat mendasari perbedaan estimasi efikasi dari uji klinis di Indonesia, Brazil, dan Turki, yaitu:
- Perbedaan distribusi karakteristik tertentu relawan di tiap negara yang mempengaruhi efikasi vaksin. Contohnya, bila diasumsikan risiko dasar relawan terkait suatu primary endpoint mempengaruhi efikasi vaksin, di mana populasi relawan dengan risiko dasar rendah (contohnya di komunitas) mendapat manfaat berbeda daripada populasi relawan yang relatif berisiko lebih tinggi (contohnya pada tenaga medis), maka uji klinis yang diadakan di lokasi dengan distribusi risiko dasar relawan berbeda dapat menunjukkan estimasi efikasi vaksin yang berbeda pula.Contoh hipotesis alasan lainnya adalah perbedaan distribusi usia relawan.
Meskipun demikian, alasan-alasan ini belum tentu benar-benar terbukti dan uji klinis vaksin pun umumnya tidak didesain untuk menjawab dengan definitif adanya kemungkinan perbedaan ini. Mayoritas perbedaan efikasi yang kita temui tidak lebih dari sekadar kebetulan saja (random chance), yang dapat kita pahami lebih lanjut di poin berikutnya. Pun jika terbukti ada perbedaan di luar random chance, ada kemungkinan perbedaan risiko dasar hanyalah suatu faktor prediksi, alih-alih faktor penyebab.
Artinya, jawaban definitif mengapa sulit dipastikan. Arah perbedaannya (misal, apakah sampel dengan risiko tinggi akan mendapat efikasi relatif lebih rendah atau sebaliknya) juga sulit diprediksi di awal walaupun bisa dieksplorasi secara deskriptif di fase analisis data.
- Variabilitas dan impresisi estimasi statistik akibat sampling dan besar sampel. Di Indonesia, estimasi efikasi sebesar 65,3% didasarkan pada 540 relawan (dari total sekitar 1.600) dengan 25 kasus Covid-19 bergejala. Ketidakpastian estimasi, yang salah satunya dapat dikuantifikasi dengan interval kepercayaan, bisa jadi masih terlalu lebar dan interval kepercayaan tersebut masih mencakup, bahkan tumpang tindih dengan, estimasi efikasi yang dilaporkan oleh peneliti di Brazil dan Turki. Hal ini terjadi karena kita hanya dapat meneliti sampel dan tidak pada semua orang di populasi target. Seiring dengan waktu dan kasus Covid-19 terakumulasi dalam uji klinis, interval kepercayaan ini akan semakin sempit dan titik efikasi saat ini (65,3%) juga akan berubah.
Di Turki, estimasi efikasi (91,25%) juga hanya berdasarkan 1.300 relawan dari total sekitar 13.000 relawan, sehingga di kemudian hari ada kemungkinan estimasi efikasi Turki juga akan berubah. Atas dasar poin kedua ini maka sebaiknya kita tidak perlu menyimpulkan terlalu dini bahwa estimasi efikasi yang berbeda antar negara benar-benar ada secara berarti.
- Bias informasi/pengukuran dalam deteksi insiden kasus Covid-19 bergejala pada uji klinis dengan sampel komunitas. Bila diasumsikan bahwa uji klinis di Brazil, yang hanya mengikutsertakan relawan tenaga medis, lebih sensitif untuk melaporkan insiden Covid-19 bergejala (termasuk gejala ringan yang mungkin lebih sulit dikenali oleh relawan awam) dan tenaga medis cenderung lebih mudah untuk mengakses fasilitas tes diagnostik Covid-19, termasuk kemungkinan perbedaan performa tes diagnostik, maka uji klinis dengan sampel tenaga medis akan menunjukkan estimasi efikasi yang lebih akurat dibanding sampel komunitas.Interpretasi demikian lebih sesuai karena primary endpoint uji klinis, sesuai dengan protokol uji klinis Sinovac sendiri, adalah untuk mengestimasi semua insiden Covid-19 bergejala, dari yang paling ringan sampai berat. Di lain pihak, pada sampel komunitas, mungkin hanya insiden dengan spektrum gejala tertentu — relatif lebih berat dan tidak mencakup semua spektrum dalam definisi primary endpoint — yang terdeteksi dan dilaporkan relawan awam. Dengan asumsi serupa, estimasi efikasi vaksin Pfizer/BioNTech atau Moderna bisa jadi menyimpang dari 95% jika mampu mencakup semua spektrum Covid-19 bergejala.
Alasan lain yang mungkin dapat menjelaskan terjadinya perbedaan efikasi adalah perbedaan desain uji klinis mendasar yang bisa berdampak pada efikasi, contohnya pada uji klinis vaksin Oxford/AstraZeneca, di mana didapatkan ketidaksengajaan perbedaan dosis vaksin, interval antara suntikan pertama dan kedua yang bervariasi, serta perbedaan placebo yang digunakan. Pada umumnya, hal ini tidak terjadi di uji klinis fase 3 karena akan menyulitkan interpretasi efek suatu vaksin. Berdasarkan apa yang tertera pada protokol uji klinis Sinovac di berbagai negara, kami menyimpulkan bahwa desain uji klinis Sinovac cukup seragam, selain faktor sampel tenaga medis di Brazil.
Idealnya, estimasi terbaik dari efikasi vaksin Sinovac akan terlihat di akhir uji klinis ketika semua data lintas negara disatukan, sehingga dapat dilakukan eksplorasi yang lebih optimal untuk melihat apakah alasan poin-poin di atas memang ada. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan dalam model estimasi bila ditemui, sehingga estimasi akhir juga akan lebih precise (interval kepercayaan lebih sempit). Perbedaan titik estimasi efikasi uji klinis di berbagai lokasi uji klinis merupakan hal yang lumrah terjadi. Contohnya dapat dilihat di hasil interim uji klinis vaksin Pfizer/BioNTech [7] [tabel 3 dirilis jurnal ilmiah NEJM] di mana efikasi vaksin ini di beberapa lokasi, seperti Argentina, Brazil, Amerika Serikat, juga berbeda tetapi interval kepercayaannya banyak tumpang tindih sehingga kita tidak dapat menyimpulkan adanya perbedaan efikasi (meskipun memang berbeda secara numerik).
Apakah sudah boleh meninggalkan 3M dan protokol kesehatan setelah mendapatkan vaksin?
Tujuan uji klinis vaksin CoronaVac, yang menguji efikasi vaksin dalam mencegah manifestasi klinis parah Covid-19 dan sakit Covid-19 bergejala, memiliki implikasi di level populasi maupun individu. Sampai sejauh ini, belum ada uji klinis vaksin Covid-19 yang dapat mengkonfirmasi apakah vaksin yang diuji dapat menurunkan risiko terinfeksi virus SARS-CoV-2 maupun risiko penularan orang yang tertular, karena uji klinis baru sampai pada penurunan risiko sakit Covid-19 bergejala. Ini menunjukkan bahwa seberapa baik proteksi vaksin-vaksin tersebut terkait risiko tertular dan menularkan virus SARS-CoV-2 belum dapat dipastikan.
Perhitungan mengenai herd immunity bergantung terhadap seberapa besar efikasi dari suatu vaksin dalam mencegah infeksi sendiri. Artinya, berdasarkan hasil uji klinis sejauh ini, perlu ditekankan bahwa prinsip 3M tetap harus dilakukan untuk mencegah penularan di masyarakat, meskipun anggota masyarakat tersebut sudah menerima 2 dosis vaksin dengan jenis dan produksi perusahaan manapun, sampai ada data yang pasti mengenai efikasi dalam pencegahan penularan dan infeksi.
Jadi apa manfaat vaksin jika belum ada kepastian bahwa vaksin dapat mencegah penularan?
Vaksin-vaksin yang sedang diuji klinis, sejauh ini, dilaporkan dapat mengurangi risiko keparahan penyakit sehingga pasien yang terinfeksi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Pemberian vaksin di masyarakat diharapkan akan mengurangi jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit, mengurangi alokasi tempat tidur dan unit pelayanan intensif (ICU) untuk pasien Covid-19, mengurangi beban kerja dan risiko kematian tenaga kesehatan, serta risiko kematian untuk pasien Covid-19 itu sendiri. Jika terinfeksi, harapannya, penerima vaksin hanya mengalami gejala ringan dan dapat melakukan perawatan mandiri di rumah.
Bagaimana menyikapi rencana vaksinasi dengan vaksin CoronaVac (Sinovac)?
Berdasarkan pengumuman hasil interim, uji klinis memperlihatkan vaksin CoronaVac memiliki efikasi di atas ambang batas WHO (yaitu 50%, dan kemungkinan dengan batas bawah interval kepercayaan di atas 30%) dan, yang tidak kalah penting, aman. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah memberikan rekomendasi kehalalan vaksin CoronaVac. Dengan ini, diharapkan tidak ada keraguan di masyarakat akan pentingnya menerima vaksin, sembari tetap menjaga prinsip 3M dan protokol kesehatan lain, karena risiko tertular dan menularkan tetap ada meskipun sudah menerima vaksin.
Mengapa harus divaksinasi?
Di Indonesia, risiko terpapar virus SARS-CoV-2 masih cukup tinggi. Data Satuan Tugas Covid-19 Indonesia melaporkan test positivity rate Indonesia berada di kisaran 30%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang yang dites, terinfeksi virus corona. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan kurangnya jumlah tes untuk populasi Indonesia, sehingga kita tidak mengetahui secara pasti jumlah orang terinfeksi yang sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, masyarakat tetap harus waspada karena kemungkinan tertular masih sangat besar dan penularan dapat terjadi di mana saja.
Vaksinasi dapat menurunkan risiko orang yang terinfeksi untuk bergejala dan dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, vaksinasi diharapkan dapat mengurangi beban rumah sakit yang kapasitasnya sangat terbatas akibat banyaknya masyarakat yang terinfeksi. Menerima vaksin Covid-19, selain upaya proteksi untuk risiko individual, juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Berita mengenai pemberian EUA untuk vaksin yang memiliki efikasi cukup baik, aman, dan terjamin kehalalannya perlu disambut dengan baik. Namun, kurangnya transparansi hasil penelitian dan telaah ilmiah dari uji klinis ini juga perlu digarisbawahi dan menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah. Transparansi hasil uji ini akan memudahkan telaah bersama dari kalangan peneliti yang harapannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terkait isu yang sensitif ini.
Referensi
- Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19 - https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization-EUA-Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html
- Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Phase III Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of treating Healthcare Professionals with the Adsorbed COVID-19 (Inactivated) Vaccine Manufactured by Sinovac – PROFISCOV: A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial - https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-020-04775-4
- Sinovac vaccine 78% effective in Brazil trial, experts call for more details - https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-sinovac/sinovac-vaccine-shows-78-efficacy-in-brazilian-trial-details-sparse-idUSKBN29C1VZ
- Brazil announces ‘fantastic’ results for Chinese-made COVID-19 vaccine, but details remain sketchy - https://www.sciencemag.org/news/2021/01/brazil-announces-fantastic-results-china-made-covid-19-vaccine-details-remain-sketchy
- CoronaVac’s Overall Efficacy in Brazil Measured at 50.4% - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/overall-efficacy-of-sinovac-vaccine-in-brazil-just-above-50?srnd=economics-vp
- COVID-19 vaccine from China’s Sinovac 91.25 per cent effective, Turkey says after trial involving 7,000 volunteers - https://www.abc.net.au/news/2020-12-25/turkey-says-covid-19-vaccine-from-chinas-sinovac-91.25-effect/13014314
- Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
